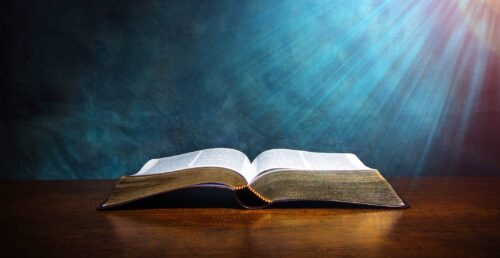Suatu ketika saya berkenalan dengan suatu keluarga saat mereka mengunjungi seorang romo yang kebetulan tinggal di satu komunitas dengan saya. Keluarga itu tampak bahagia. Kedua anaknya sedang menjalani kuliah di luar negeri dengan prestasi yang luar biasa. Anak perempuannya yang sulung mirip dengan ayahnya, sedangkan anak laki-lakinya mirip dengan ibunya.
Beberapa bulan kemudian setelah pertemuan itu, ibu dari keluarga tersebut menghubungi saya dan ingin bertemu. Ibu ini sedang kesulitan memahami anak putrinya yang sudah lulus kuliah dan sedang bekerja di luar negeri. Akhirnya, saya pun menerima ibu itu dan suaminya di ruang tamu pastoran. Sang ibu mengungkapkan rasa takut bahwa ia akan kehilangan putrinya.
Dari sharing ibu itu, saya menangkap bahwa anaknya lesbian. Meskipun anaknya telah melela kepada kedua orangtuanya, ibunya secara cukup jelas menyangkal dan menolak bahwa anaknya seorang lesbian. Padahal, si anak sudah mencoba untuk menceritakan bagaimana dia bisa sampai pada kesimpulan tersebut.
Sang ibu tidak dapat menerima identitas seksual anaknya dan bahkan membuat rasionalisasi bahwa anaknya mungkin ‘salah gaul’. Ia mengatakan bahwa putrinya memiliki jiwa sosial yang besar. Mungkin karena dia terlalu berempati dengan komunitas LGBTQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer), dia akhirnya ‘tertular’.
“Meskipun anaknya telah melela kepada kedua orangtuanya, ibunya secara cukup jelas menyangkal dan menolak bahwa anaknya seorang lesbian.”
Pendapat sang Ibu justru melukai perasaan putrinya. Terjadilah perdebatan dahsyat yang mengakibatkan relasi ibu dan anak membeku. Sang ibu bingung dan khawatir bahwa ia akan kehilangan putri satu-satunya yang ia cintai. Ibunya menyangkal identitas seksual putrinya, namun putrinya tidak dapat menyangkal identitas seksual dirinya sendiri. Lalu ibunya berharap bahwa saya, sebagai seorang frater muda, bisa ‘menyadarkan’ putrinya yang mungkin ‘tersesat’ dalam dunia orang dewasa di negara lain.
Saya pun bingung mau bagaimana. Sebagai seorang penengah, pastinya saya harus berada dalam posisi yang netral tanpa memberikan opini ‘moral’. Who am I to judge?
Akhirnya, setelah kontak dengan putrinya via Instagram. Saya mendengarkan pergulatan yang ia hadapi sendiri dalam memahami identitas seksualitasnya.
Orang-orang heteroseksual yang merupakan mayoritas sekaligus menjadi norma masyarakat secara umum, pastilahsulit memahami adanya orang-orang homoseksual.
Seorang hetero melihat bahwa kebanyakan dari orang-orang sekelilingnya adalah hetero. Baginya, manusia yang wajar adalah mereka yang memiliki ketertarikan eksklusif pada lawan jenis. Jika ia mengaitkan heteroseksualitas sebagai kodrat manusia, maka semua yang berbeda akan dianggap menyalahi kodrat tersebut.
Pada sisi lain, seorang homoseksual yang hidup di dunia hetero akan merasa dirinya aneh bahkan tertekan karena ia tidak dapat mengubah orientasi seksualnya ke hetero. Celakanya, ada banyak dari kaum homoseksual yang mengikuti program-program “penyembuhan” yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga yang mengklaim dapat menjadikan mereka ‘normal’. Namun, pada kenyataannya, orientasi seksual tidak dapat diubah.
Akhirnya, tidak sedikit dari mereka mengelabui masyarakat dan membohongi dirinya dengan topeng hetero. Bahayanya, penyangkalan diri yang dilakukan secara terus menerus secara tidak sadar dapat menjerumuskan sang homoseksual ke dalam jurang self-hate (benci-diri) yang ia gali sendiri.
Dalam kasus ekstrem, tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Namun, kebanyakan dari mereka memilih untuk hidup dalam kepalsuan agar mereka dapat diterima dalam masyarakat hetero. Sedangkan mereka yang ingin tampil apa adanya akan menghadapi hidup yang penuh perjuangan dengan masyarakat yang tidak mau menerima diri mereka.
Masyarakat Indonesia pada umumnya kurang menerima keberadaan kaum LGBTQ. Survei yang dilakukan oleh lembaga riset global Pew Research Center pada 2019 menunjukkan bahwa hanya 9 persen masyarakat Indonesia yang menerima keberadaan homoseksualitas. Orientasi seksual, sayangnya, bukanlah sesuatu hal yang tampak secara fisik. Seandainya mereka memiliki fitur yang tampak dari lahir secara fisik, mungkin itu akan lebih mempermudah orang-orang untuk melihat ini sebagai hal lahiriah seperti halnya tai lalat atau tekstur rambut.
Meskipun demikian, realitas ketertarikan seksual yang dialami oleh kaum LGBTQ merupakan satu hal yang tidak dapat disangkal oleh orang itu sendiri. Namun hal tersebut seringkali disalahpahami oleh orang lain sebagai pilihan hidup yang egois.
“Survei yang dilakukan oleh lembaga riset global Pew Research Center pada 2019 menunjukkan bahwa hanya 9 persen masyarakat Indonesia yang menerima keberadaan homoseksualitas.”
Saya dapat memaklumi bahwa pasangan suami istri hetero yang mendatangi saya menganggap pengakuan anaknya sebagai seorang homoseksual itu sebuah fase ‘coba-coba’ dengan orientasi seksual. Tetapi kenyataan yang dihadapi oleh anaknya adalah bahwa dirinya benar-benar tidak memiliki kecenderungan heteroseksual. Dia sendiri sempat mengalami periode dalam masa remajanya untuk memastikan apakah ia benar-benar seorang heteroseksual atau bukan.
Dia telah mencoba pacaran beberapa kali dengan lawan jenis, tetapi ia tidak merasakan kedekatan emosional maupun ketertarikan seksual. Dia bahkan mencoba untuk berdoa dan berdevosi agar ia ‘disembuhkan’ dari kecenderungan ini, namun segala upaya itu tidak membuahkan hasil. Ia sempat mempertanyakan mengapa Tuhan menciptakan dia demikian, dan apabila ini hanya merupakan cobaan, mengapa cobaan itu tidak kunjung berakhir?
Periode pergulatan identitas, bukanlah periode yang menyenangkan baginya karena segala upaya untuk memiliki ketertarikan dengan lawan jenisnya berakhir dengan kegagalan dan benci diri. Hal ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa kaum LGBTQ dilihat sebagai ‘orang-orang cacat’ oleh masyarakat umum. Penolakan diri yang dilakukan secara terus menerus malahan berdampak negatif pada kesehatan mentalnya.
Pandangan negatif terhadap dirinya mulai berubah ketika ia menerima orientasi seksualnya sebagai bagian dari dirinya yang telah diciptakan oleh Tuhan. Hal ini semakin ia amini dengan adanya dukungan emosional dari para sahabat dan beberapa anggota keluarga yang mau mendengarkan dan memahami pergulatannya.
Dukungan dari beberapa orang terdekatnya merupakan wujud nyata kasih Tuhan pada dirinya. Hal-hal tersebut justru semakin mendorongnya menjadi pribadi yang lebih utuh dan tangguh. Ia pun bisa semakin berkembang dalam aspek kepribadian dan karir karena sudah merasa lebih terbebaskan dari tuntutan masyarakat yang membebani hatinya. Namun, ibunya masih belum dapat menerima dia secara utuh. Sang ibu dan anak sama-sama keras kepala, sayangnya orientasi seksual dari kedua orangtuanya tidak diwarisi oleh putrinya.
Kedua sisi memang memiliki kompleksitasnya masing-masing. Hal ini cukup menantang bagi saya untuk menciptakan sebuah jembatan antara ibu dan anak yang bisa menyangga dirinya sendiri tanpa perantaraan seorang penengah. Satu-satunya harapan adalah hubungan darah yang mereka miliki. Namun, sungguh tidak ideal jika satu sisi menutup diri untuk memahami sisi yang lain.
Ketakutan sang ibu yang terbangun atas pandangan negatif terhadap kaum LGBTQ melampaui kebutuhan anaknya untuk dipahami. Sang Ibu takut anaknya akan memiliki masa depan yang suram.
Mungkin ia sendiri memiliki pandangan bahwa orang-orang LGBTQ tidak memiliki gaya hidup yang sehat; bahwa mereka tidak bisa berkeluarga secara wajar. Mereka bisa saja mengadopsi anak atau menggunakan prosedur teknologi biomedis yang canggih, tetapi apakah mereka bisa merawat dan mendidik anak secara baik?
Namun segala kesimpulan itu adalah hasil dari permenungan sang ibu tanpa melibatkan pandangan anaknya. Dasar dari ketakutan itu memang cinta terhadap anaknya, namun sepertinya sang Ibu terlalu terpengaruhi oleh pandangan negatif terhadap kaum LGBTQ. Ia takut putrinya tidak akan memiliki hidup yang bahagia dan bermartabat.
Pandangan negatif inilah yang perlu diubah dan jika ibu ini tetap berpegang pada pandangannya, anaknya justru tidak akan bahagia atau, dalam kasus ekstrim, memutus hubungan keluarga lalu menghilang.
Sayangnya, mayoritas dari pandangan anti-LGBTQ terbentuk dari beberapa penggalan ayat Alkitab yang dipakai untuk mencap mereka sebagai musuh hukum kodrat yang harus dibasmi. Namun, jika kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kasih, apakah itu tidak bertentangan dengan ajaran Kristiani yang jelas-jelas menentang kekerasan?
Orang-orang juga suka lupa bahwa kekerasan verbal melalui pem-bully-an sering terjadi kepada anak-anak yang memiliki perilaku yang dianggap kurang maskulin atau feminin. Ujaran-ujaran kebencian terhadap mereka menciptakan sebuah pandangan bahwa dunia tidak menerima mereka apa adanya dan sebuah kaca yang mencerminkan diri mereka sebagai seorang ‘monster’.
“Namun, jika kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kasih, apakah itu tidak bertentangan dengan ajaran Kristiani yang jelas-jelas menentang kekerasan?”
Sebagai orang Kristiani, kita dipanggil untuk meniru teladan Yesus dalam kapasitas kita masing-masing. Yesus selalu menunjukkan jalur cinta kasih dan pengampunan serta menghardik mereka yang menganggap dirinya suci. Yesus justru menunjukkan sikap kerendahan hati dan keterbukaan pada kelompok yang dianggap rendah oleh masyarakat, misalnya para pemungut cukai dan pelacur.
Lalu apakah kita akan meniru teladan prinsip hidup Yesus dan menerapkannya hanya kepada orang tertentu? Yesus dalam Alkitab ditampilkan sebagai seseorang yang memberi kesempatan bagi lawan dialognya untuk berbicara dan dipahami dalam suasana yang saling menghargai. Orang telanjang yang kesurupan saja dia dekati.
Sayangnya, banyak dari umat yang menemukan dirinya sebagai LGBTQ menjadi seperti domba yang terpisah dari kawanannya. Mereka dalam kesendirianya secara ketakutan mencari jawaban dan tempat yang mau menerima mereka apa adanya. Umat lain yang bukan LGBTQ lebih mudah untuk membungkam dan mengutuk ketimbang mendengarkan perspektif saudara-saudari mereka yang LGBTQ dan bagaimana mereka bisa menyadari orientasi seksual tersebut.
Mungkin kita sebagai Gereja kurang seperti Yesus yang ingin memahami orang-orang yang abnormal. Mungkin kita lebih tertarik untuk berkarya bagi orang-orang normatif saja, karena tentunya itu tidak akan menuai kontroversi.
Namun, apakah yang dapat kita lakukan seandainya yang abnormal itu adalah orang yang amat kita sayangi atau bahkan ketika yang abnormal itu adalah diri kita sendiri? Apakah kita mau mendengarkan dan merangkul mereka atau diri kita sendiri yang bukan bagian dari ‘norma’ masyarakat?
Artikel ini juga muncul dalam bahasa Inggris. Anda dapat menemukan versi itu di sini.